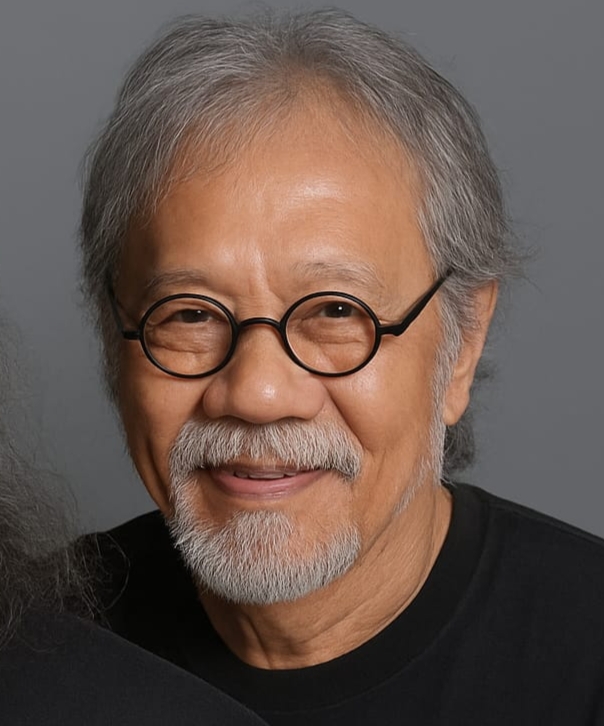Oleh : Bambang Iss
Ada secuil kisah dari seorang pemulung. Namanya Raji. Seorang pria separuh baya. Bertubuh kurus, tapi tak pernah berhenti mengisap rokok walau berjalan berkilo-kilometer jauhnya. Kantung bagor disampirkan dipundak dan berhenti di tempat pembuangan sampah rumahan. Lalu mengaislah tangannya di situ.
Hampir setiap hari aku berpapasan dengan Raji selepas subuh. Kami sama-sama “pengukur” jalan, maksudnya sama-sama berjalan kaki. Namun kami berbeda maksud. Aku berjalan kaki demi kebugaran, sedang dia untuk hidup setidaknya untuk hari itu dengan mendapatkan barang buangan yang bisa dijual lagi.
Diantara beberapa pemulung yang berseliweran, dalam pandanganku, Raji ini unik. Seorang bocah laki-laki usia sekitar 4 atau 5 tahun, selalu _nginthil_ mengikuti Raji. Si bocah yang terlihat tanpa sendal atau alas kaki itu berusaha merendengi langkah Raji sementara laki-laki itu dengan sabar memperlambat jalan agar mereka tak saling mendahului.
“_Niki lare kula_..(ini anak saya),” kata Raji.
“Kenapa ikut bekerja?”
Mulailah Raji berkisah ihwal mengapa anak lelaknya itu ikut bekerja, berjalan kaki berjauh-jauh, tak beralas kaki pula. Sementara anak-anak seusia dia masih terlelap di atas ranjang yang empuk di dalam kehangatan ibu, si buyung ini tersaruk di jalanan.
“Di rumah tidak ada yang momong..” suara Raji parau. “Istri saya meninggal,”
Aku tercekat. Istri Raji meninggal tanpa sebab. Karenanya Raji harus tetap hidup, agatlr di biyung tetaombisa makan, bekerjalah Raji apa adanya. Bekerja memulung sebagai pilihan, seperti yang sudah dilakukan selama ini kembali diteruskan.
Seriap bersitatap ketemu Raji dan buyungnya, aku diam-diam mencuri dengar apa yang mereka bicarakan selama berjalan kaki itu.
Ah, mereka ternyata tidak saling bercengkerama seperti galibnya anak bapak. Tapi mereka bicara tentang hidup.
“Ini untuk jajan..” kataku memberikan sedikit uang kepada si buyung.
Memang tadi kulihat sekilas wajah Raji _sumiringah_.
Tapi dia tetap saja sedih. Kakinya menendang sebutir kerikil. Berserak. (BIS)